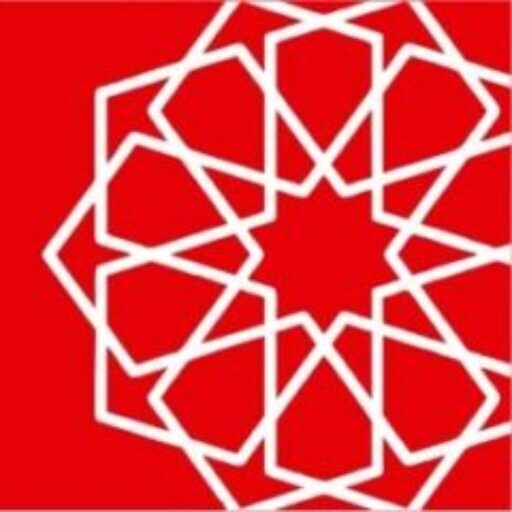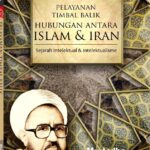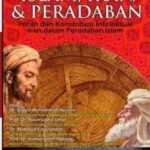Penjelasan Muthahhari dalam sub bab “Tentang Berperang” berangkat dari kesalahpahaman orang-orang yang menganggap Islam sebagai agama perang. Konsekuensi pemikiran ini berujung pada keyakinan bahwa Islam adalah agama yang tidak mendukung kedamaian dan menentang kemanusiaan. Penilaian ini datang dari orang-orang yang memahami seruan perang dalam Islam sebatas permukaan saja. Tak melihat bagaimana Islam memberi syarat yang ketat untuk terlaksananya peperangan itu.
Dalam uraiannya, Muthahhari memaparkan bagaimana realitas sosial kita ini tak hanya diisi oleh orang-orang yang berakal. Realitas memperlihatkan kepada kita, betapa banyak orang yang hidup dengan menuhankan hawa nafsunya. Penderitaan yang lahir akibat penjajahan yang terjadi sepanjang sejarah adalah bukti nyata dari eksisnya manusia yang hidup dengan menunhankan hawa nafsunya itu.
Manusia-manusia yang telah berkhianat kepada akalnya hingga terbutakan hatinya, akan melakukan apa saja untuk memenuhi hasrat duniawinya. Sekalipun itu harus melalui perusakan dan penindasan terhadap makhluk yang lain.
Manusia yang telah sampai di titik ini, adalah manusia yang telah melakukan kedzaliman, melanggar hak dan batas-batas kemanusiaan, menciptakan penderitaan bagi yang lain. Maka berdiam diri atas ini, adalah sebuah bentuk kedzaliman lainnya. Rasionalitas kita secara alamiah akan menuntut untuk melakukan perlawanan agar kedzaliman ini dapat teratasi.
Kurang lebih melalui logika inilah Islam menghalalkan apa yang disebut sebagai peperangan. Ia bukan sebuah bentuk agresi, memulai penyerangan terhadap pihak lain. Ia adalah bentuk pertahanan, pembelaan diri, dan penolakan terhadap kedzaliman yang mengacam hak seseorang.
Muthahhari menekankan pentingnya kita untuk membedakan antara damai dan menyerah. Bahwa menyerukan hidup damai, tak berarti menyerah terhadap kedzaliman. “Perdamaian adalah hidup berdampingan dengan orang lain secara mulia, sedangkan menyerah bukan hidup berdampingan secara mulia, tetapi hidup berdampingan secara hina”.
Diamnya seseorang ketika menyaksikan penindasan terjadi, adalah sebuah bentuk dukungan terhadap penindasan itu sendiri. Sehingga, dalam menghadapi kedzaliman hanya ada dua jalan. Mengambil jalur perlawanan atau hidup menjadi penindas.
Dalam peristiwa Asyura, kelompok Yazid adalah penindas. Dan Imam Husain hadir sebagai pihak yang melawan penindasan itu. Sayangnya, masyarakat Kufah yang telah meminta Imam Husain untuk datang menjadi Imam mereka, tidak dalam kondisi siap untuk berjuang melawan penindas Yazid. Mereka tidak siap untuk mengorbankan diri dan kepentingannya di jalan kebenaran, jalan Imam Husain. Maka berakhirlah mereka ke dalam kelompok yang turut menyerang Imam Husain di Karbala, dan selebihnya ‘diam’ menyaksikan kesyahidan Imam dan keluarganya yang di awal mereka harapkan menjadi Imam untuk dibaiat.
Refleksi pribadi dalam menuliskan ini, mungkin saya pun boleh jadi ketika berada di posisi masyarakat Kufah, saya belum berada pada pihak yang berani untuk berdiri dalam barisan Imam Husain, dan menerima segala bentuk tekanan dari kelompok para penindas.
Dalam diri, masih berkecamuk perang antara Imam dan Yazid. Imam yang mewakili dorongan kelayakan akal, dan Yazid yang mewakili dorongan hawa nafsu. Dan jelas saja, seringkali Yazid dibiarkan bahkan secara sadar terfasilitasi untuk tumbuh dalam jiwa.
Maka peperangan Imam dan Yazid, tak hanya hidup dalam sejarah realitas eksternal. Peperangan itu pun hidup dalam diri kita. Setiap hari, di setiap pilihan yang muncul di hadapan kita. Dan saya percaya, tak akan ada manusia yang bisa berdiri di barisan Imam ketika masih hidup Yazid-Yazid kecil di dalam jiwanya.
Maka sesungguhnya, setiap hari adalah asyura, dan setiap tempat adalah karbala.
Nur Afika Firanti, S.Kom
Santriwati Takhasus RCF-RCRF 2025