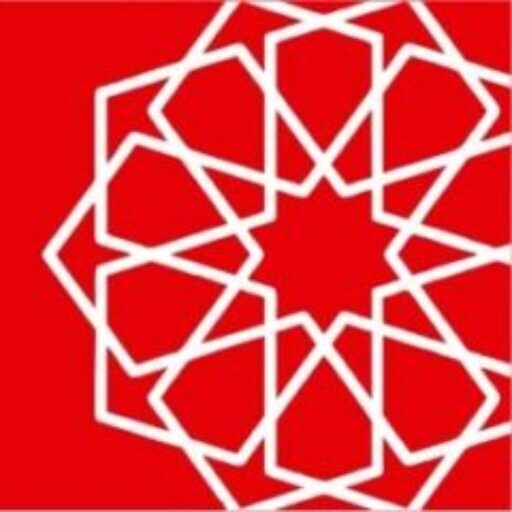Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam. Penganutnya diperintahkan berbuat baik dan menjauhi keburukan. Harapan atas kondisi sosial masyarakat Indonesia yang lebih baik menjadi lebih terbuka. Sebab bukankah kita negara dengan mayoritas penduduk muslim? (Baca: Satu Data Kemenag RI, 2022).
Nyatanya, merajalelanya korupsi, tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga, hingga merebaknya kasus pelecehan oleh oknum tokoh agama, dan banyak kasus lainnya, justru membuat kita akhirnya ragu. Inikah kondisi sosial wilayah yang dihuni oleh mayoritas muslim itu?
Banyak orang yang tertindas. Banyak orang yang dirampas haknya di negara ini. Banyak orang yang hidup di garis kemiskinan. Mengapa?
Bukankah Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan? Sudahkah Indonesia dengan mayoritas penduduk muslimnya, mencerminkan wajah kemanusiaan, keadilan, kasih dan rahmat bagi seluruh alam itu?
Amat perlu rasanya kita merefleksi kembali keberagamaan yang kita pegang. Apakah islam sebagai rahmat telah tumbuh dalam jiwa dan berbuah dalam tindakan kita? Atau justru islam sebagai agama kita saat ini tak lebih dari sekadar klaim keberagamaan belaka?
Atau jika ingin lebih jauh, mungkinkah kita perlu menggugat, “benarkah islam adalah agama yang membawa kebaikan dan kedamaian?
Fenomena orang beragama yang justru bertindak merusak, membuat banyak orang ragu, mungkin kita pun termasuk. Benarkah agama (islam), adalah sebaik-baik jalan hidup bagi manusia untuk bertemu dengan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan?
Tak jarang ditemukan orang yang tidak bertuhan dan tak beragama, namun tindakannya justru tampak lebih “beragama” dibanding mereka yang meneriakkan agama dengan lantang.
Mereka yang merawat alam, peduli dengan hewan dan memberi makan yang kelaparan, justru tak jarang adalah orang yang dipandang sinis dari mereka yang jumawa dengan keberagamaannya.
Lantas darimana kebaikan yang datang dari orang-orang ‘tak beragama’ ini? Apakah ada kebaikan yang tak datang dari Tuhan?
Kita juga sampai pada pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah agama dan nilai-nilai kemanusiaan adalah dua hal yang tak sejalan? Apakah agama di satu sisi adalah satu hal, dan nilai-nilai kemanusiaan adalah hal lainnya? Atau mungkinkah justru nilai-nilai kemanusiaan bahkan boleh jadi bertentangan dengan agama?
Jika ya, maka seharusnya agama dengan sejumlah aturannya memang tak layak dijadikan sebagai jalan hidup. Mungkin akan lebih mudah hidup lepas dari aturan agama namun tetap memegang nilai-nilai kemanusiaan (humanisme). Jika ini benar, maka tinggallah agama sebagai sebuah ajaran dogmatis belaka yang sama sekali tak memiliki fungsi dalam melakukan perbaikan (transformasi) dalam masyarakat.
Ajaran tauhid dalam islam, ajaran yang pertama kali disampaikan oleh sang utusan, Rasulullah Saw. Sebelum shalat, zakat dan kewajiban lainnya, adalah pilar bagi kemanusiaan. “Wahai manusia! Katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah”, menjadi pondasi dalam ajaran islam.
Menurut Murtadha Muthahhari, selama permasalahan ini tidak mempunyai akar di dalam jiwa dan hati seseorang, maka semua bagian yang merupakan cabang-cabang agama belum mempunyai dasar.
Sampai di sini, permasalahan kita ada dua. Pertama, fenomena orang beragama yang dalam tindakannya sama sekali tak mencerminkan keberagamaannya. Boleh jadi, beragama sebatas formalitas belaka.
Hilangnya sisi batin agama (termasuk kesadaran tauhid) yang justru menjadi hal mendasar, membuat agama menjadi momok yang menakutkan bagi kelompok yang lain. Implikasinya, agama hanya akan menampilkan wajah yang kaku bahkan mengkhianati kemanusiaan.
Melihat kondisi ini, kita perlu sadar bahwa pembahasan tauhid yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sisi batin islam, menjadi satu isu penting yang layak untuk direfleksikan kembali oleh muslim dewasa ini. Alhasil, tauhid tak berakhir menjadi sekadar ucapan di mulut kaum muslim.
Masalah yang kedua termasuk konsekuensi dari pokok masalah pertama, dan inilah inti pembahasan kita. Ketika agama kehilangan sisi batin akibat rapuhnya pondasi tauhid, maka lahirlah pemisahan antara nilai-nilai kemanusiaan dan agama.
Padahal ketika kita mau merenungi lebih dalam, keduanya adalah dua hal yang tak terpisah. Bahkan ajaran tauhid bukan saja pondasi agama, tauhid justru menjadi pondasi bagi kemanusiaan itu sendiri.
Ajaran tauhid membicarakan tentang bagaimana segala hal berasal dari dan akan kembali kepada-Nya. Segala perbuatan akan dikembalikan bukan untuk kepentingan diri (ego pribadi), kekasih, keluarga, penguasa, melainkan hanya kepada-Nya. Di sini jiwa menemukan titik kestabilan, sebab aktifitasnya tak lagi diintervensi oleh hawa nafsu hewaniah dan kepentingan pribadinya, melainkan fitrah insaninya yang berorientasi kepada yang tak terbatas, Yang Maha Mutlak.
Namun, darimana datangnya kebaikan (nilai-nilai kemanusiaan) bagi ‘orang yang tak bertauhid’?
Alamiahnya, tak ada manusia yang menginginkan keburukan. Dan sebaliknya, semua manusia menginginkan kebaikan, minimal untuk dirinya sendiri. Demikian pula pandangan Muthahhari, bahwa secara fitrah, manusia memiliki kecenderungan terhadap kebaikan. Sehingga sebenarnya manusia selalu terpanggil ke arah aktualisasi nilai-nilai kemanusiaan itu (insan).
Hanya saja, pada diri manusia juga terdapat kecenderungan hewaniah, termasuk hawa nafsu dan ego pribadi yang seringkali membuat manusia lalai dari panggilan fitrah insaninya.
Posisi jiwa yang ambigu inilah yang terkadang membuat seorang manusia di satu waktu dapat menjadi manusia yang berbuat baik kepada sesama, namun pada waktu yang lain, ia tenggelam dalam ego dan pengaruh hawa nafsu hewaninya, hadirlah tindakan eksploitasi, korupsi, kekerasan, dan segala perbuatan negatif yang sempat kita singgung di awal.
Tiap orang dapat berbuat kebaikan hingga bahkan rela mengorbankan kepentingan dirinya. Hanya saja, satu pegangan nilai sebagai tujuan dari kebaikan yang dilakukan (motif) mesti dimiliki. Ketika motif kebaikan yang kita lakukan adalah untuk manusia, orientasi semacam ini tak akan melahirkan tindakan kebaikan yang stabil, sebab bisa jadi kita terjebak pada kebaikan yang hanya dilakukan terbatas pada orang tertentu. Orientasinya bisa jadi karena kita memiliki kepentingan dengan orang tersebut. Salah satunya ialah harapan akan timbal balik dari kebaikan kita.
Maka tak jarang, kita menemukan orang lain atau bahkan mungkin diri kita sendiri, yang kecewa ketika telah berbuat baik kepada orang lain, namun tak menerima balasan kebaikan yang sama dari orang tersebut. Tentu ini juga satu pilihan. Sayangnya, kebaikan seperti ini menjadi tidak stabil sebab masih dikontrol oleh aspek psikologis (suka/tidak suka). Kebaikan kita hanya menjadi rahmat bagi hawa nafsu kita, bukan seluruh alam.
Kita berharap dapat sampai pada tindakan kebaikan (aplikasi nilai-nilai kemanusiaan) yang stabil. Bahwa kita akan berbuat baik tanpa memandang siapa sosok itu, baik dia kaya atau berkecukupan, keluarga atau bukan, pejabat ataupun rakyat biasa, entah orang itu akan membalas kebaikan kita atau tidak. Sehingga kebaikan telah menjadi moral pribadi kita yang terlepas dari bagaimana orang lain berlaku terhadap kita.
Pada tahap ini, ketika kebaikan yang kita amini tak lagi bermotif pada apa pun (material), maka mesti kita memiliki suatu konsep nilai yang lebih tinggi, dan menjadi acuan kita dalam berbuat baik, apapun namanya. Hal tersebut menjadi satu idealitas bagi jiwa, menjadi satu-satunya orientasi dalam berbagai tindakan kita.
Akhirnya, syariat dalam agama sebenarnya menjadi jalan bagi jiwa agar dapat menyingkap fitrah insani yang telah dititipkan pada setiap diri. Pelaksanaan syariat dengan sejumlah aturannya menjadi latihan bagi jiwa untuk dapat meninggalkan hawa nafsu dan ego yang mengekang manusia, dan membuatnya jauh dari dirinya yang sejati (insan).
Ketika jiwa manusia tak lagi menjadi budak dari hawa nafsu dan ego rendahnya (hewaniah), maka ia pun dapat melakukan pengorbanan demi satu konsep yang dia idealkan tersebut. Agama menyebut konsep ini sebagai tauhid, bahwa semua sebab adalah dia, karena semuanya berasal dan akan kembali kepada-Nya.
Wallahualam bissawab.