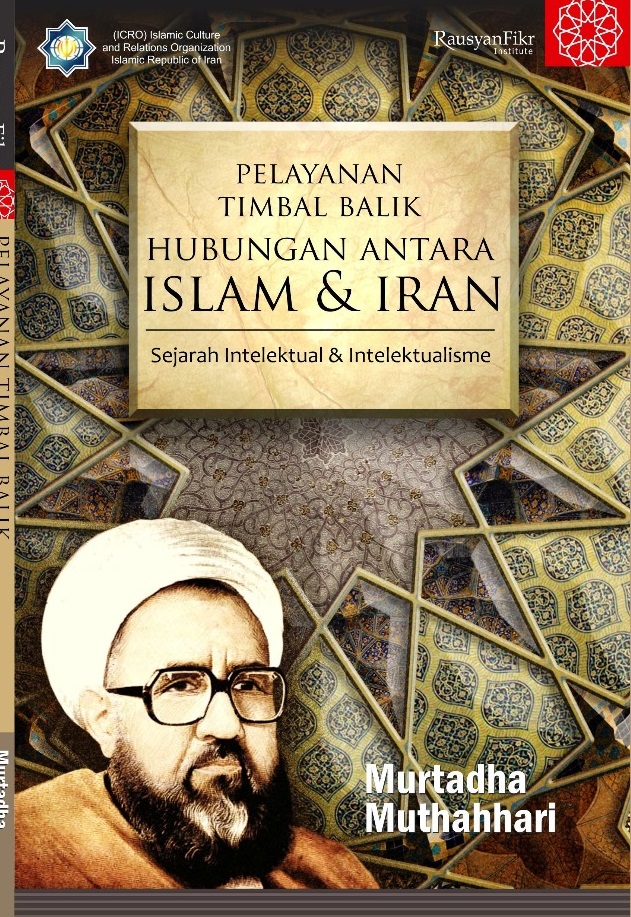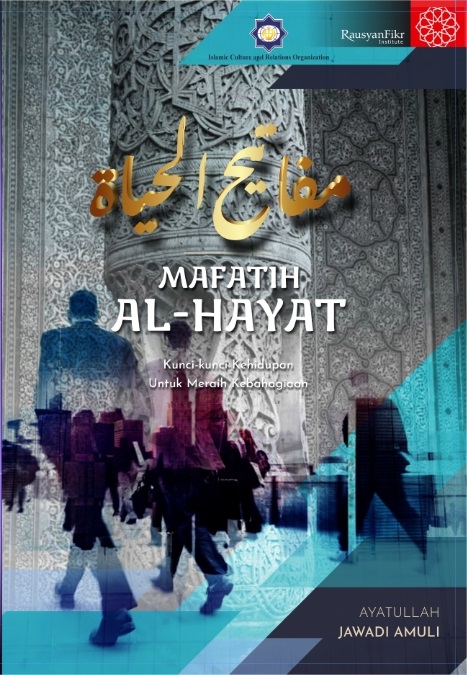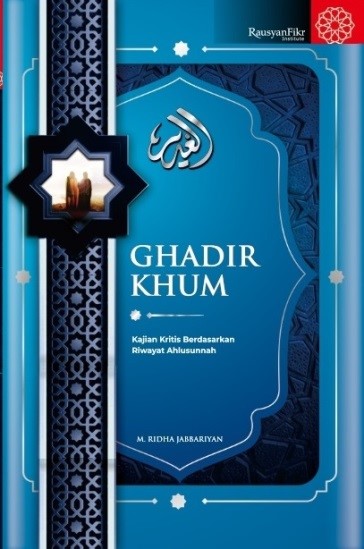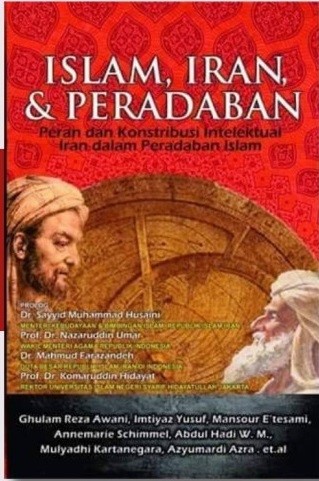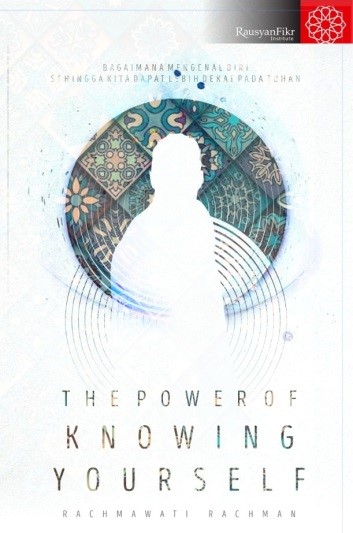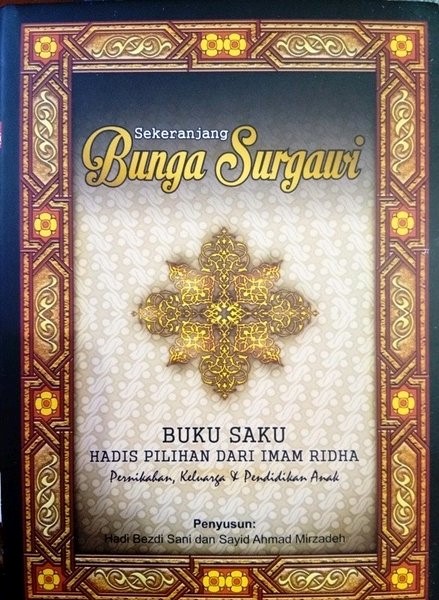Epistemologi dan agama berwatak sosial
Nilai hakiki daripada sebuah pengetahuan terdapat diluar pengetahuan itu sendiri. Dikarenakan, segala sesuatu yang tersantir oleh mental manusia secara azali tidak sebagaimana realitas yang disantirkan dari luar (eksternal). Sehingga, apakah kita hanya ingin hidup sekedar apa yang kita pikirkan dan apa yang dipikirkan oleh orang lain terkait kita (sudut pandang). Begitupun, dengan rupa agama bahwa pastilah agama memiliki suatu tujuan pada dirinya dan akan menemukan bentuknya pada realitas.
Sehingga, yang dimaksud orang beragama yaitu, kesesuaian antara yang dipikirkan dan realitas (praktis). Oleh karena itu, terdapat relevansi antara fungsi epistemologi (pengetahuan) dan agama. Relevansi tersebut ketika tujuan hakiki daripada pengetahuan manusia dan agama adalah ketika segala sesuatu yang dikonsepsikan berhasil menemukan bentuknya (terobjektifikasi) pada sisi tindakan (perbuatan). Artinya, tidak ada lagi jarak yang membatasi antara sesuatu yang terpahami (fungsi epistemologi) begitupun pemahaman terkait agama. Bagaikan, sebuah pengetahuan telah bermakna predikatif. Maka, pengetahuan melingkupi segala sesuatu, segala acuan, segala perkara yang mampu menjaga kita (keterjagaan) sebagai fungsi ontologis (teoritis).
Apa yang ingin ditekankan dalam agama? Yaitu, terkait bagaimana pemahaman agama tersebut. Artinya, siapapun yang memiliki keyakinan terkait sesuatu apapun terlebih agama mestilah memiliki dasar simpulan atau mukadimah pengetahuan di dalamnya. Sehingga, sebenarnya yang paling dimungkinkan untuk ditumbuhkan menjadi kultur (budaya) terhadap kondisi atau situasi keberagaman keyakinan di alam merupakan budaya diskursus dan dialog. Agar cara berkeyakinan manusia tidak cenderung pasif dalam beragama atau tidak jumud, terus diperbaharui dan tidak terkesan menjauhkan agama dari kehidupan bersama (sosial).
Selanjutnya, sejauh ini apa persoalan terhadap simpulan keyakinan beragama yang perlu diperbaharui (refleksi)?
Pertama, permasalahan seputar epistemologi. Karena, sejauh ini persoalan mendasar apakah agama memiliki pijakan rasionalitas dan bagaimana agama terimajinasikan sebagai sebuah kendaraan untuk kembali kepada fitrah (suci) sebagai dasar penciptaan manusia dengan kemandirian (rasionalitas). Sehingga, pada posisi itulah akan agama bernilai sebagai suatu rangkaian perjalanan untuk kembali kepada jiwa yang satu (mutmainnah).
Kedua, melihat kembali dasar-dasar kepercayaan dengan epistemologi (pengetahuan/kesadaran) agar agama yang diyakini juga memiliki nilai makro (sosial). Mengapa demikian, karena secara lahiriah (alami) memang manusia berhubungan dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, pengetahuan (epistemologi) juga memiliki watak atau kedudukan secara sosial begitupun dengan sebuah agama.
Kemudian, berangkat dari kecenderungan (fenomena) sekarang beberapa orang beragama hanya untuk agama itu sendiri. Artinya, keyakinan agama hanya demi kepentingan yang terkait eksistensi dirinya sendiri (individualistis). Sementara, apa yang dimaksud dengan sebuah kesadaran beragama yang predikatif (terkukuhkan) semestinya, akan andil (berpihak) dalam suatu perubahan, kemajuan, atau transformasi sosial dan hidup bersama masyarakat dalam keadilan.
Lantas pertanyaanya, dimana posisi dan kedudukan para pemuka agama atau lembaga agama yang terkait? Dimana keberpihakan atau bentuk objektifikasi dari keyakinan keagamaanya (tauhid)? Jika, melihat jauh kebelakang (sejarah) kenabian dan setelahnya. Bahwa agama merupakan tindakan (perbuatan) pelayanan. Pelayanan yang seperti apa? Yakni, membawa (mengantarkan) masyarakat kepada kesempurnaan (kelayakan).
Titik tekannya, dengan begitu jelas bahwa pengetahuan tidak mungkin hanya untuk pengetahuan itu sendiri dan agama tidak hanya untuk agama yang bersifat sendiri-sendiri (subjektif) atau (eksklusif). Oleh karena itu, titik pertemuan dari cara mengobjektifikasi pengetahuan dan agama yang paling real (nyata) adalah terlihat pada tindakan atau menjadi ideologis. Ideologis disini artinya, memiliki keterkaitan kepada kesucian/spiritualitas (keharusan universal). Sehingga, dengan dasar kesadaran itu keberadaan manusia dalam bertindak bukan karena kepentingan sendiri-sendiri atau segelintir kelompok saja.
* Epistemologi pengalaman beragama : Murtadha Muthahhari, Prof. Kuntowijoyo, dan Allamah Iqbal
Apabila menelisik dan mengkaji pemikiran, Allahuyarham (Prof. Kuntowijoyo) pada beberapa karyanya yang menurut penulis terdapat suatu pengetahuan teoritis atau metodelogi disebut dengan strukturalisme transendental yang dapat diuji secara bersama-sama, namun tidak akan dijelaskan secara terperinci dalam tulisan kali ini karena hanya bersifat pengantar.
Strukturalisme transendental sebagai paradigma untuk memahami kedudukan beragama. Secara sederhana Kuntowijoyo berupaya menjelaskan bahwa struktur dalam agama seperti, shalat, haji, puasa, dan zakat dapat membawa jiwa (nafs) manusia kepada transendensi (sesuatu yang lebih tinggi—hakikat). Artinya, terdapat ruang pertautan dan kehamornisan yang terjalin meski diantara kedua konsep yang secara teoritis berbeda antara alam immaterial (batin) dan alam raga (fisikal).
Begitupun juga, terlihat sedikit titik pertemuan yang sama dengan struktur pemikiran Murtadha Muthahhari dalam melihat relasi agama dengan nilai-nilai kemanusiaan yang (fitrah/suci). Bahwa kedudukan agama tidak terpisahkan secara metodelogi dan substansi untuk mengantarkan nilai-nilai kemanusiaan yang fitrah (suci) untuk diaktualkan pada realitas.
Dengan begitu, agama tidak akan pernah memiliki unsur kausa/sebab final terhadapnya. Mengapa, karena manusia senantiasa berjalan menggunakan kendaraan agama tersebut sebagai unsur (atribut) penyempurnaan jiwanya. Artinya, atas dasar pemahaman kemandirian berpikir menghasilkan sebuah sistem nilai atau di syaratkan (terikat) pada agama. Sehingga, semakin bertambah dan tinggi capaian spiritualitas seseorang dalam beragama semestinya secara teoritis akan aktif (progresif) pada kehidupan yang dijalani atau dilalui.
Konsekuensi akan timbul, ketika hanya berhenti pada agama sebagai tujuan akhir (final). Kemungkinan yang terdekat bahwa agama hanya akan dijadikan sebagai ajang saling klaim siapa yang paling beragama, mengingingkan (imajinasi) masuk surga atau neraka, dan eksploitasi (penindasan). Pertanyaanya, mengapa agama hanya sekedar disempitkan pada hal seperti itu tanpa segi yang lebih tinggi (transenden)?
Begitupun dengan Allamah Iqbal bahwa bagaimana beliau mentransformasikan pengalaman beragama itu sebagai imajinasi (atribut) penyempurnaan manusia dan autentik. Artinya, pengalaman dalam beragama merupakan wadah (ruang) membawa transformasi batin manusia dan masyarakat secara lebih besar (sosial).
Namun, mengapa sekarang agama telah menjadi ruang kapitalisasi. Misalnya, haji dan umroh terkapitalisasi melalui usaha travel haji dan umroh. Makna haji yang direduksi dari makna irfan/hakikat (Ali Syariati). Padahal, mukadimah dari kewajiban pada tubuh agama adalah kewajiban pula. Begitupun haji tersebut, artinya sebelum berhaji mestilah memikirkan apakah 40 tetangga disekitarnya telah dipastikan bahwa tidak lagi dalam keadaan lapar.
Akan tetapi, fenomena yang terjadi sekarang berhaji atau bertuhan tanpa ada rasa kepedulian sosial (empati). Dengan demikian, melaksanakan haji tanpa ada tahapan landasan kemanusiaan (realis). Padahal, yang fundamental atau mendasar ialah, menanamkan dan memiliki kesadaran nilai-nilai kemanusiaan pada sesama manusia yang terletak di sekitarnya agar kemudian secara perlahan-lahan bertransformasi menjadi nilai ketuhanan (ilahiah).
Oleh karena itu, apakah yang beragama itu hanya di isi oleh imajinasi mampu dilaksanakan dalam ukuran sah dan tidaknya sebagaimana pada dalam fiqh-nya (tindakan perbuatan). Akan tetapi, tidak memenuhi sisi irfani (batin) dari sebuah struktur agama tersebut. Sehingga, struktur agama hanya dijadikan sebagai ritus-ritus (formalitas) atau nilai simbolik. Artinya, mampu mencapai kepada kedalaman hati (qalbu) sebagai spirit manusia dalam beragama dapat juga disebut jalan lain agama.
Rajab
Santri Takhassus 2024-2025
PPM Muthahhari Yogykarta